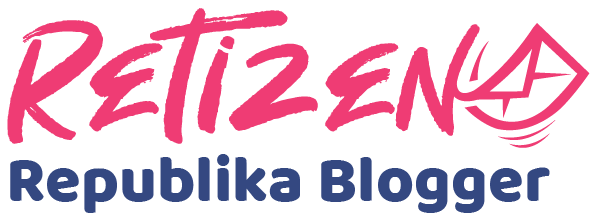Kepala Sekolah di Persimpangan Jalan: Birokrat atau Arsitek Masa Depan?

BISNISTIME.COM, JAKARTA – Jumat (03/10/2025) Bayangkan seorang arsitek andal yang memiliki cetak biru megah untuk membangun sebuah mahakarya. Namun, alih-alih meletakkan batu pertama, ia justru menghabiskan hari-harinya tenggelam dalam tumpukan formulir perizinan. Metafora inilah yang melukiskan dilema besar kepala sekolah di Indonesia saat ini. Mereka dididik untuk menjadi arsitek masa depan generasi, namun realitas seringkali memaksa mereka menjadi birokrat yang terperangkap di balik meja.
Di satu sisi, dunia akademis membekali mereka dengan teori-teori kepemimpinan yang ideal. Ada kepemimpinan transformasional yang mengajak untuk bermimpi besar dan mengubah budaya sekolah. Ada pula kepemimpinan instruksional yang menempatkan kepala sekolah sebagai coach utama bagi para guru, memastikan setiap jam pelajaran berkualitas. Teori-teori seperti servant leadership (pemimpin yang melayani) dan distributed leadership (kepemimpinan yang berbagi) melengkapi gambaran ideal seorang nakhoda pendidikan yang inspiratif dan kolaboratif.
Namun, cetak biru yang indah itu seringkali berbenturan dengan tembok birokrasi yang kokoh. Ironisnya, seorang pemimpin yang seharusnya paling dekat dengan denyut nadi pembelajaran justru dijauhkan oleh beban administratif.
Artikel ini ditulis oleh: Trisia Loli maulana (Diajukan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Kepemimpinan & Pengambilan Keputusan, Dosen Pengampu: Dr. Dr. Dra. Hj. Neng Nurhaemah, M.Pd., S.Pd.)
Ketika Visi Tergerus Tumpukan Kertas
Kenyataan di lapangan menunjukkan gambaran yang kontras. Data Kemendikbudristek pada tahun 2023 menjadi bukti nyata: lebih dari 60% waktu kepala sekolah habis untuk urusan administratif. Mulai dari laporan Dana BOS yang rumit, persiapan akreditasi yang menyita energi, hingga berbagai formulir lainnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Suyanto & Jihad (2021) yang mengungkap bagaimana para kepala sekolah di berbagai daerah merasa kewalahan menyeimbangkan peran manajerial dengan tugas pedagogis mereka.
Akibatnya, muncullah beberapa fenomena yang menghambat kemajuan:
- Visi Hanya Sebatas Pajangan: Visi dan misi sekolah yang disusun dengan indah akhirnya hanya menjadi hiasan di papan pengumuman. Energinya habis sebelum visi tersebut sempat diterjemahkan menjadi aksi nyata di ruang kelas.
- Supervisi yang Kehilangan Makna: Kunjungan kelas atau supervisi yang seharusnya menjadi momen coaching yang memberdayakan guru, seringkali terdegradasi menjadi sekadar formalitas untuk mengisi instrumen penilaian. Dialog mendalam tentang metode mengajar tergantikan oleh centang pada lembar evaluasi.
- Panggung Tunggal Sang Pemimpin: Alih-alih mendistribusikan kepemimpinan, banyak sekolah masih terjebak dalam pola hierarkis. Kepala sekolah menjadi satu-satunya pusat komando, sementara guru diposisikan sebagai pelaksana. Akibatnya, potensi inovasi dari akar rumput menjadi sulit tumbuh.
Oase di Tengah Gurun Birokrasi
Meski tantangan begitu besar, bukan berarti tidak ada harapan. Di berbagai penjuru Indonesia, ada kepala sekolah yang berhasil mendobrak tembok ini dan menjadi oase di tengah gurun birokrasi.
Dalam program Sekolah Penggerak, kita melihat para pemimpin yang berani memangkas rapat-rapat seremonial dan menggantinya dengan forum refleksi pembelajaran. Di beberapa sekolah di Yogyakarta dan Jawa Barat, komunitas belajar antar guru (learning community) tumbuh subur, diinisiasi oleh kepala sekolah yang percaya bahwa guru adalah aset utama. Contoh inspiratif lain datang dari SMAN 2 Semarang, di mana kepala sekolah mendorong lahirnya proyek-proyek lintas disiplin yang dipimpin oleh guru, membuktikan bahwa kepemimpinan bisa dan harus dibagi.
Membangun Kembali Arsitektur Kepemimpinan
Untuk membebaskan lebih banyak kepala sekolah dari jebakan administratif dan mengembalikan mereka pada peran sejatinya, beberapa langkah strategis mutlak diperlukan:
- Digitalisasi dan Penyederhanaan Birokrasi: Pemerintah harus mengakselerasi sistem pelaporan berbasis digital yang terintegrasi, mengurangi tumpang tindih dokumen, dan memangkas alur birokrasi yang tidak efisien.
- Pendampingan Intensif, Bukan Sekadar Workshop: Pelatihan kepemimpinan harus bergeser dari model seminar singkat ke pendampingan jangka panjang yang fokus pada praktik nyata di lapangan, seperti manajemen perubahan dan supervisi klinis.
- Membuka Ruang Kolaborasi: Budaya "satu komando" harus diubah menjadi budaya kolaboratif. Libatkan guru, tenaga kependidikan, bahkan siswa dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk menumbuhkan rasa memiliki.
- Mengembalikan Ruh Pendidik: Kepala sekolah perlu didukung untuk menjadi pemimpin moral yang berani memprioritaskan kualitas pembelajaran di atas tuntutan citra atau "branding" sekolah yang dangkal.

Pada akhirnya, bangsa ini tidak hanya butuh manajer sekolah yang pandai mengelola anggaran. Kita butuh para arsitek pendidikan yang mampu merancang ekosistem belajar yang memanusiakan, menginspirasi, dan membebaskan potensi setiap anak Indonesia. Tugas kita bersama adalah memberikan mereka ruang, alat, dan kepercayaan untuk mulai membangun.
Referensi
- Bass, B. M. (1990). From transactional to transformational leadership: Learning to share the vision. Organizational Dynamics.
- Hallinger, P. (2011). Leadership for learning: Lessons from 40 years of empirical research. Journal of Educational Administration.
- Spillane, J. P. (2006). Distributed leadership. Jossey-Bass.
- Suyanto & Jihad, A. (2021). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia. Jurnal Manajemen Pendidikan.
- Kemendikbudristek (2023). Laporan Tahunan Pendidikan Indonesia.
- Greenleaf, R. K. (1977). Servant Leadership. Paulist Press.


 Properti - 03 Oct 2025
Properti - 03 Oct 2025